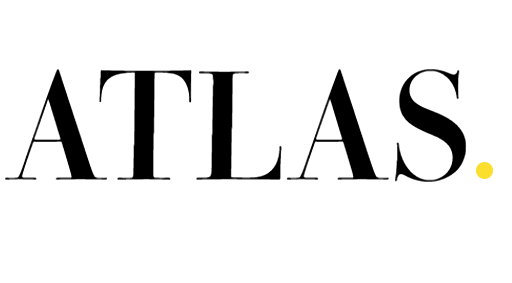Pada saat Laila Mumtaz menyatakan ingin ikut orangtua, mati bersama laut Samudera Hindia itu, tiba-tiba aku melihat sirip ikan hiu mendekati kami. Aku mengajak Mumtaz untuk menyelamatkan diri dengan menghalau hiu besar itu. Nmaun, Mumtaz tidak mau menghalau, bahkan dia seakan menyerahkan dirinya kepada hiu.
Kerajaan Laut Nyai Tiara Ratu - Kapal tongkang Ocean Dream berangkat pukul 09.45 dari dermaga Khumara, Pakistan Timur, 23 Agustus 2013 menuju Chrismas Island, Australia. Setelah sandar dua hari di Pulau Panaitan, Banten, Indonesia, seminggu kemudian, kapal berlayar menyusuri Banten Selatan, mampir di Pulau Tinjil lalu lanjut ke wilayah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.
Kapal berkapasitas 50 rang bertonase 10 ton ini berbendera Indonesia, milik Robert Hamidan, orang Jakarta yang bermukim di Phuket, Thailand. robert Hamidan bisnis bidang perkapalan kecil dan losmen di Phuket. Karena Robert Hamidan berteman dengan papaku, maka aku diterima bekerja di usaha kapal miliknya yang mangkal di Maladewa.
Aku mengelola Ocean Dream dan bertugas di Maladewa. Ketika kapal ini akan ke Australia membawa 50 orang imigran gelap yang akan meminta suaka politik, aku sedang cuti panjang, penasaran ingin ikut berlayar dengan kapal berwarna merah itu. Walau aku mampu membeli tiket pesawat terbang, karena ingin bertualang dengan laut, maka aku ikut berlayar bersama empat awak kapal lain anak buah Pak Robert Hamidan.
Mula-mula pelayaran itu sangat indah. Aku mendengarkan musik kesukaanku selama perjalanan. Aku mendapatkan makanan enak di kapal, yang dibeli oleh awak kapal setiap sandar melempar jangkar. Namun, setelah meninggalkan Pulau Tinjil, Banten Selatan, Wilayah Samudera Hindia, angin badai datang. Angin berkecepatan tinggi, rata-rata 150 kilometer per jam.
Karena kecepatan angin yang begitu tinggi, maka gelombang laut pun sangatlah tinggi, membumbung hingga sembilan meter. Kapal pun oleng dan nakhoda kehilangan kendali. Kapten panik dan kapalpun kemasukan angin yang melimpah ruah. Kapal oleng dan terbanting. Tak ayal, kapalpun tenggelanm dan 50 penumpang, termasuk anak-anak, masuk ke laut.
Aku pasrahkan hidupku kepada Allah dan berusaha berenang sebisanya untuk menyelamatkan diri. Tetapi berenang di tengah gelombang besar, sangat sulit dan terasa tubuhku tidak bergerak sedikitpun. Aku berdzikir dan terus bermunajat kepada Allah Azza Wajalla memohon keselamatan diri. Allah ternyata mendengar pintaku Jeritan hatiku didengar dan aku menemukan sebuah drup plastik kecil dan aku memeluk drup plastik warna biru yang biasa digunakan menampung air tawar itu.
Beberapa jam aku terapung di permukaan laut, aku melihat puluhan mayat wanita dan anak-anak yang mengambang. Salah seorang diantaranya, aku perhatikan masih hidup dan aku mengajaknya untuk bergelayutan di drum. Wanita remaja itu bergelayut bersamaku di drum dan kutekan punggungnya, agar di amuntahkan air di dalam perutnya dan diapun muntah air laut. Setelah muntah, dia agak kuat bersamaku memegang drum dan kami terus terapung, tidak tahu entah ke mana arahnya.
Gadis yang belakangan ku ketahui bernama Laila Mumtaz itu telah kehilangan kedua orangtuanya, berikut adiknya yang masih balita. Dia terus-terusan menangis namun aku berusaha meneduhkan perasaan sedihnya. Begitu dia melihat mayat ibu, ayah, dan adiknya, dia berusaha meraih tiga mayat itu. Aku berusaha membantu, tetapi gagal. Gelombang laut membawa tiga mayat itu ke arah lain, dan kami pun kehilangan pandangan.
Tiga mayat itu di bawa ombak dan menghilang dari pandangan kami. Drum yang kami naiki terpontang panting terus di dorong oleh angin badai menuju ke arah yang tidak jelas. Malam pun tiba dan keadaan laut menjadi gelap gulita. Sementara itu, gelombang mengecil, ombak mereda dan lautpun menjadi tenang.
Untunglah, malam itu muncul bulan yang terang dari timur. Bulan itu terus merangkak dan menerangi laut. Kami berdua terus mengapung, sambil berdoa dengan cara masing-masing. Namun Laila Mumtaz berdoa sambil terus menangis. Dia sangat sedih kehilangan orang tua dan adiknya, bahkan dia ingin mati pula bersama mereka.
Pada saat Laila Mumtaz menyatakan ingin ikut orangtua, mati bersama di laut Samudera Hindia itu, tiba-tiba aku melihat sirip ikan hiu mendekati kami. Aku mengajak Mumtaz untuk menyelamatkan diri dengan menghalau hiu besar itu. Nmaun Mumtaz tidak mau menghalau, bahkan dia seakan menyerahkan dirinya kepada hiu.
Benar saja, di tengah sinar bulan purnama terang, aku melihat dengan kasat mata, Mumtaz ditelan hiu. Mumtaz ditelan bulat-bulat di depan mataku dan aku melihat dia dibawa ke dasar laut.
Jantungku berdebar-debar hebat dan pikiranku tiba mengambang. Antara rasa sedih kehilangan Mumtaz dan rasa takut berkecamuk hebat di dalam diirku. Aku terus memegang erat drum biru itu dan berusaha sebisa mungkin mengayuhkan kaki, agar drum bergerak walau hanya sedikit.
Sebagai wanita yang lemah, aku yang sejak kecil hoby bertualang menjemput tantangan, malam itu berusaha bangkit walau aku dalam keadaan terpuruk. Ayah dan ibuku, ketika mereka masih hidup, selalu jengkel dengan kegiatanku bertualang ini. Mereka marah sekali kalau aku naik gunung, memanjat tebing dan mancing di laut. Aku selalu dilarang karena aku wanita sementara teman-temanku semuanya pria.
Mama lebih dulu meninggal. Lalu papaku memilih hidup menduda dan tidak mau menikah lagi. Saat aku bekerja di Maladewa dengan Pak Robert Hamidan temannya, papaku menyusul mama. Papa meninggal karena sakit jantung di rumah sakit Harapan Kita Jakarta.
Sejak mama dan papa ku wafat, aku jarang pulang ke Jakarta. Rumah peninggalan papa dijual oleh abangku tertua, Bang Hengku Truman, yang penjudi dan pemabok. Hubunganku dengan Bang Hengky tidak begitu baik, maka itu aku malas ke rumahnya bila aku pulang ke Indonesia. Aku lebih suka ke rumah Tente Ema, adik mamaku yang tinggal di Metro Lampung Tengah.
Kini aku terapung-apung di laut dan tertidur karena lelah. Ombak sudah mulai tenang dan bulan purnama beranjak ke barat. Aku tertidur pulas dalam keadaan mengapung di atas drum. Ketika bulan berganti matahari di timur, aku terjaga dan aku mendekati sebuah pulau kecil. Pulau itu adalah pulau kosong yang hanya ditumbuhi pohon-pohon perdu dan bakau yang rimbun. pulau tersebut ternyata Pulau Dili, pulau kecil di barat Pulau Tinjil, Banten Selatan.
Dalam keadaan lemas karena terapung 24 jam di laut, aku mengayuh sebisa kakiku untuk mencapai pulau. Karena dorongan ombak, aku mencapai Pulau Dili dan merebahkan diriku ke pasir pantai. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, mencari manusia yang mungkin bisa menolongku yang lemah dan lemas. Tetapi pulau itu benar-benar pulau kosong yang tidak berpenghuni. Pulau itu hanya sesekali disinggahi nelyan, pemancing dan kapal-kapal kecil penangkap ikan.
Aku didekati oleh beberapa biawak besar pengkuni Pulau Dili. Biawak itu mungkin mengira aku makanan enak yang siap untuk disantap. Namun, ketika aku menggerakkan kaki, puluhan biawak itu kabur ke dalam hutan.
Aku teringat bagaimana sadisnya ikan hiu memakan temanku Mumtaz. Ada rasa trauma dan phobia yang sangat dalam bergelayut dalam diriku. Betapa biadabnya hiu itu, sadis dan buas, memakan wanita remaja yang tak bersalah di depan mataku. Dan aku emrasa sangat menyesal tidak bisa menolong Mumtaz, tidak bisa membantunya untuk menyelamatkan diri dari hiu yang ganas.
Matahari makin mencorong menuju tengah langit. Aku berusaha bangkit untuk mencari air tawar dan makan. Tetapi makanan apa yang aku dapatkan di pulau kosong itu? Entahlah, namun aku harus bisa menemukan makanan.
Dengan tertatih aku berusaha berjalan ke dalam hutan. Meninggalkan pantai berpasir itu. Drum warna biru yang menolong menyelamatkanku, aku naikkan ke darat dan aku akan bawa ke manapun aku tinggal. Drum plastik itu menjadi teman hidupku dan menjadi saksi bisu tentang perjuanganku untuk hidup.
Sesampainya di dalam hutan Pulau Dili, aku melihat sebuah rumah mewah bergaya bangunan Paseo De Garsia, berpilar empat, berukir monotheis dengan gambar bintang di tengahnya. Aku mencubit tubuhku, men-check apakah aku bermimpi atau sdang benar-benar berada di alam nyata. Arkian, ternyata kulitku sakit aku cubit dan aku tidak sedang bermimpi. Aku masuk ke beranda rumah itu dan mengetuk. Seorang nyonya cantik dan muda, membukakan pintu dan mengajak aku masuk ke dalam.
Nyonya cantik yang memperkenalkan diri bernama Tiara Ratu Pandanwangi itu mengajak aku ke meja maknnya. Meja makan dari batu marmer dan kursi kirstal itu berisi banyak makanan, lauk pauk enak, buah-buahan dan kue-kue lezat. Aku dipersilahkan makan dan meminum minuman jus buah di meja indah itu. Aku lalu melakukan apa yang ditawarkan. Aku minum sepuasnya dan makan sepuasnya.
Setelah kenyang, aku diajaknya ngobrol di ruang tamu. Ruang tamu itu penuh dengan perhiasan emas, mutiara dan intan original. Lampu-lmapu kristal mewah di atas ruang tamu itu, dengan sofa terbuat dari kulit beruang kutub.
Setelah berjam-jam aku ngobrol, Nyonya Tiara Ratu Pandanwangi memberikan ku beberapa kepingan emas, intan dan berlian di dalam sebuah peti. Peti berwarna merah itu diserahkannya kepadaku dan harus aku bawa pulang. Setelah itu, dia memanggil sopir kapal yach yang juga wanita, untuk mengantarkan aku ke Muara Binuangeun, Malimping, Banten Kidul.
Sopir Yacht, kapal kecil bermesin bernama Nyimas Banowati itu mengantarkan aku meninggalkan Pulau Dili menuju Muara Binuangeun. Drum biru aku masukkan ke kapal dan Nyimas memeprtanyakan tentang mengapa aku membawa drum itu. Setelah aku ceritakan, dia memahami dan tidak melanjutkan tanya yang lebih melebar kepadaku.
Setelah dua jam perjalanan laut, sampailah senja hari di Muara Binuangeun. Saat aku mau berpisah dengan Nyimas Banowati, gadi scantik itu memberikan amplop besar kepadaku. Katanya titipan dari Nyai Tiara Ratu Pandanwanti. Aku meniram amplop besar yang belakangan aku ketahui adalah uang berjumlah Rp 50 juta pecahan seratus ribuan untuk ongkosku pulang.
Aku mencium Nyimas dan diapun segera berlayar dengan wajah sedih. Karena angkutan sepi, aku mencari mobil sewaan untuk mengantarkan aku ke Jakarta. Sebuah mobil kijang inova aku sewa Rp 2 juta mengantarkan aku ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, aku ke toko emas Engkoh Wiliam di Senen dan Engkoh Wiliam meyakinkan aku bahwa emas yang kubawa emas murni 24 karat dan dianjurkan dijual ke PT. Logam Mulia.
Begitu juga dengan intan, mutiara dan berlian dan di dalam peti, semuanya asli dan bernilai jual Rp 5 Miliyar. Uang lima milyar aku berikan semuanya ke panti asuhan, anak yatim dan rumah kompo di Bogor. Aku tidak memegang sepeserpun uang itu karena pikirku, uang itu bukanlah hak aku, tapi hak orang miskin yang dititipkan Allah melalui Nyai Tiara Ratu Pandanwangi.
Mengetahui aku mendapatkan uang banyak, emas, intan dan berlian, abangku yang suka judi mengajakku ke Pulau Dili. Dia ingin menemui Nyai Tiara Ratu Pandanwangi dan mau meminta uang. Selain uang, dia juga meminta emas, intan dan mutiara dan berlian yang ada di rumah Nyai Tiara Ratu Pandanwangi.
Karena aku memang akan berangkat ke Maladewa setelah cuti, maka aku mau pamit kepada Nyai Tiara Ratu yang baik hati. Aku berangkat bersama abangku ke Muara Binuangeun lalu menyewa kapal nelayan ke Pulau Dili. Arkian, ternyata rumah Nyai Tiara Ratu dan kapal yacht yang dikendalikan Nyimas Banowati, tidak ada lagi. Pulau Dili ternyata tidak berpenghuni dan rumah mewah serba kristal dan emas itu, tidak ada secara nyata.
"Mbak ke dalam rumah itu sebenarnya masuk ke dalam kerajaan gaib. Di pulau Dili itu ada kerajaan gaib Nyai Tiara Ratu Pandanwangi yang kaya raya. Nyai Tiara Ratu Pandanwangi itu adalah bangsa lelembut, bangsa jin laut yang menguasai pulau ini. Beliau hanya maujud untuk orang-orang pilihannya. Mbak pada waktu itu ditolong dan dijadikan saudaranya. Tetapi, karena datang dengan motivasi uang, Nyai Tiara Ratu Pandanwangi, tidak mau maujud lagi. Abang Mbak ini, punya motivasi minta uang dan emas itu. Tetapi Nyai Tiara tidak mau memberi maka itu dia tidak mau maujud," kata pemilik perahu nelayan yang sudah mengantarkan kami, Kang Encep Nasarudin, warga Muara Biuangeun, yang sangat paham akan penghuni gaib Pulau Dili dan Pulau Tinjil itu.
Setelah samapi di jakarta, abangku marah-marah dan jengkel kepadaku. Padahal aku tidak bersalah soal Nyai Ratu Tiara itu dan dialah yang ngotot untuk menemui. Kini pada tahun 2013 ini, terakhir bulan Agustus lalu, aku terus didatangi Nyai Tiara Ratu Pandanwangi, penguasa gaib Pulau Dili itu dan memberikanku uang di saat aku terdesak kebutuhan.
Sekarang ini, karena Pak Robert ditangkap polisi Phuket, Thailand akibat kecelakaan maut dan kapal tanpa izin berlayar, maka aku tidak bekerja lagi di perusahaan Pak Robert di Maladewa. Aku menganggur di Maladewa dan bekerja sebagai penasehat spiritual usahawan setempat.
Walau aku hidup miskin di negeri orang, namun setiap bulan purnama ke 14, Nyai Tiara Ratu Pandanwangi selalu datang kepadaku memberikan kepadaku uang dan emas. Dari Nyai pula, aku dapat membantu pengobatan warga Maladewa dengan cara-cara perdukunan. Bahkah, Alhamdulillah, aku dapat memberikan nasehat jitu dalam berbisnis. Setiap yang meminta nasehatku, usahanya maju pesat dan memberikan tanda terima kasih berbentuk uang kepadaku. Terimakasih ya Allah, terima kasih Nyai Tiara Ratu Pandanwangi.
(Kisah ini dialami oleh Mariana Farida, Tia Aweni D. Paramitha menulis cerita itu untuk Kita semua)
D, Tia Aweni. 2013. Majalah Misteri Edisi 568. Jakarta: Yayasan Sinar Berdiri Jaya.