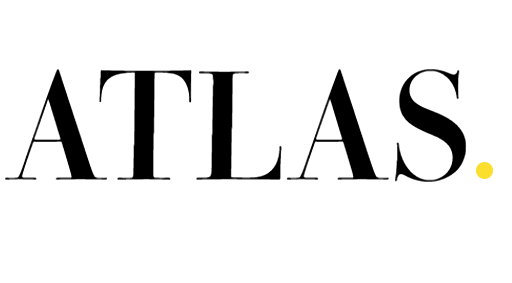Hampir semua warga kampungku mengatakan bahwa aku orang miskin. Banyak pula orang yang menyebut bahwa aku adalah orang yang sangat tidak mampu. Bahkan, banyak orang kampung menyebut bahwa aku adalah orang yang sangat papa, orang yang sangat menderita kekurangan ekonomi.
Tongkat Kayu Sakti Warisan Mbah Buyut - Tidak kurang pula, orang mengatakan bahwa aku, adalah seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan yang parah. Tapi, aku pasrah, aku menerima saja anggapan banyak warga dan banyak orang itu, karena aku memang demikian adanya. Ya, memang aku adalah orang miskin, bahkan teramat miskin, jauh lebih miskin dari orang-orang yang tergolong miskin di seluruh Indonesia. Memang penghasilanku per-bulan, sebagai buruh tani, kurang dari Rp 300 ribu.
Dengan begitu, per-hari penghasilanku hanya sekitar Rp 10 Ribu, sedangkan anakku berjumlah enam orang. Semuanya harus bersekolah dan semuanya harus makan. Maka itu, anak tebesarku, Halimah, terpaksa membantu aku mencari uang. Anak gadisku itu, dengan sangat keras ikutan bekerja untuk menyambung hidup kami. Halimah menjadi buruh tukang cuci dan tukang strika di rumah tetangga.
Pagi-pagi, Halimah berangkat sekolah, siang hari dia mencuci pakaian dan menyetrika pada keluarga Nur Aliem Halvaima. Gajinya, Rp 150 ribu per-bulan, cukup untuk biaya sekolahnya di SMP dan sedikit untuk membantu adik-adiknya yang belum bisa mencari uang.
Amirudin, anakku nomor dua, yang juga masih di SMP kelas dua, bekerja sebagai tukang cuci motor di tempat steam. Bayarannya, hanya Rp 2000 per-motor. Bila mendapat tiga motor per-hari, gajinya per-hari hanya Rp 6000. Semakin banyak mendapatkan jatah cucian motor, semakin bertambah penghasilan Amirudin. Amirudin pun, dapat membantu adik-adiknya membeli pakaian, uang jajan dan biaya sekolah, selain untuk biaya sendiri.
Sejak suamiku meninggal, aku bekerja keras banting tulang mencari uang. Tidak ada saudara, tetangga dan famili yang bisa membantu kami. Semua warga sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tidak mungkin dapat menolong kami. Lagi pula, bagi kami, orang Komering, malu untuk meminta-minta. Jangankan meminta, dibantu orang memberikan makanan pun, rasanya kami sangat malu.
Untuk itu, beberapa kali aku terpaksa menolak tawaran bantuan warga karena rasa malu ini. Prinsip saya, kami boleh hidup miskin, tapi harga diri tetap harus terjaga baik. Tidak boleh dan sangat pantang meminta-minta. Kecuali, keadaan sangat memaksa. Misalnya, saat anak saya sakit panas tinggi, di mana saya terpaksa pinjam uang untuk berobat ke dokter kecamatan. Itupun benar-benar minjam. Di mana setelah itu, uang pinjaman untuk berobat itu, saya kembalikan lagi pada yang meminjamkan.
Melihat kami hidup susah, hidup centang perenang setelah suami meninggal, memang banyak orang yang prihatin dan simpati. Tapi, aku hanya bisa menghargai rasa simpati itu dan aku menampik semua bantuan yang sekiranya akan menjadi masalah di belakang itu. Sebab, banyak orang membantu untuk pamer, seakan mereka sangat sosial dan perduli. Banyak yang membantu justru untuk menghina kami, di mana setelah itu mereka mengungkit-ungkit bantuan mereka untuk menghina kami. Karena pertimbangan itulah, maka, aku lebih baik memilih kerja keras daripada hanya menadah bantuan orang.
Setelah tamat SMP, anak tertuaku, Halimah Sakdiah, menikah. Mukhlis Amran, saudara jauh dari almarhum suamiku, meminang Halimah dan membawanya tinggal di Pandeglang, provinsi Banten. Mukhlis bekerja di bank kabupaten dan hidup lumayan baik. Artinya, gajinya cukup untuk menghidupi Halimah dan mereka sudah punya rumah di kota Pandeglang.
pernikahan mukhlis dan Halimah dilangsungkan di rumahku di Belitang, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dengan mengundang sekitar 500 orang. Rumah kami yang kecil dan kumuh, dibuatkan tenda yang bagus dan Mukhlis mengeluarkan tabungannya yang cukup untuk acara pesta itu.
Setelah tiga tahun bermukim di Kota Pandeglang, Halimah dan Mukhlis memiliki seorang anak. Cucuku itu berjenis kelamin laki-laki dan wajahnya mirip sekali dengan almarhum suamiku, kakeknya. Setelah pulang kampung saat lebaran, Mukhlis meminta aku membuka rekening bank. Aku membuka rekening bank Mahkota Abadi, sebutlah begitu, yang diurus bersama Mukhlis dan dimasukkannya uang Rp 6 juta untuk kebutuhan kami.
Aku diajari oleh Mukhlis, menantuku, bagaimana caranya mengambil uang, bagaimana cara transfer dan bagaimana caranya menabung. Selain kartu ATM, aku juga diberikan catatan buku tabungan dengan jumlah saldo di dalamnya. Saldo Rp 6.000.000, dan uang itu tidak saya gunakan sebelum ada keperluan yang mendesak, sesuai pesan dari menantuku, yang memberikan uang itu.
Perjalanan hidup terus mengelinding bagaikan roda bajaj yang terus berputar berkejaran dengan waktu. Walau anak-anakku sudah dapat dibantu oleh Halimah dan Mukhlis, namun aku tetap menjalani pekerjaan sebagai buruh tani. Aku terus bekerja dari pagi hingga petang di ladang kelapa sawit dan ladang perkebunan karet di daerah Belitang, kampung kami. Hidupku terus berpanas matahari dan bermandikan keringat kelelahan menoreh karet dan memanen serta membersihkan rumput perkebunan kelapa sawit.
Setiap malam aku bertahajut, berdoa dan berdzikir, mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla, meminta bantuan, pertolongan-Nya agar aku dan anak-anakku semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup dan kebahagiaan serta kedamaian. Anak-anakku yan gsudah aqil baliq, semianya melakukan sholat lima waktu dan juga sembahyang sunah seperti tahajud, sholat dhuha setiap matahari mulai terbit. Tiada hari tanpa doa dan tiada hari tanpa meminta kepada Sang Pencipta dan setiap hari aku terus berkerja keras, tanpa berhenti satu jam pun.
Pada saat membutuhkan uang untuk mengganti genteng yang bocor dan pecah, aku mengambil uang ke bank Mahkota Abadi. Setelah menggesek kartu ATM dan memencet nomor PIN, maka keluarlah uang Rp 1.000.000 yang saya butuhkan. Setelah keluar struknya, aku melihat saldo tabunganku tersisa Rp 5.000.000, dari jumlah Rp 6.000.000 pemberian menantuku.
Uang berjumlah sejuta itu lalu aku belikan genteng di toko material, beberapa sak seman dan cat water proof anti bocor. Selebihnya akan digunakan untuk membayar tukang, Bang Subardi, tukang bangunan di sebelah ujung kampung kami.
Setelah selesai memasang genteng dan mencat bagian bocor dengan water proof, aku lalu menelpon Halimah dan Mukhlis, menceritakan bahwa aku memakai uang pemberian mereka sebesar satu juta untuk merenovasi rumah yang bocor.
"Mama pakai saja uang itu sesuka Mama, karena uang itu sudah menjadi hak Mama dan adik-adik", kata Mukhlis, di Pandeglang, kepadaku via telpon seluler. Bahkan Mukhlis menambahkan jika uang itu sudah habis, Mukhlis akan mentrasnfer lagi untuk persediaan kami.
"Mama harus selalu ada uang di bank yang sewaktu-waktu Mama bisa gunakan. Jangan lagi, saat anak-anak sakit, Mama lari ke sana ke mari meminjam uang kepada tetangga", desis Mukhlis, meyakinkan aku. Aku sangat bersyukur kepada Allah SWT, di mana mendapatkan mantu yang begitu baik. Mukhlis bukan saja membahagiakan istrinya, anakku, tapi keluarga besar istrinya pun, diperhatikannya dengan baik.
Di perkebunan kelapa sawit, aku bertemu dengan seorang kakek tua bertubuh bongkok. Kakek itu bertubuh hitam legam karena terbakar matahari, memakai topi caping, berbaju sorjan Jawa dan bercelana sedengkul membawa tongkat kayu setigi.
Sebenarnya, Mukhlis dan Halimah Sakdiyah tidak lagi menginginkan aku bekerja di ladang karet dan ladang kelapa sawit. Mereka prihatin dan sangat kasihan melihat aku yang setiap hari bekerja keras bermandikan keringat dan berjemur matahari untuk mencari uang sekedar membeli sesuap nasi. Mereka bisa mengirim uang kebutuhan kami dan bisa mencukupi semua kebutuhan kami.
Tapi, karena aku terbiasa bekerja, terbiasa beraktifitas, rasanya tidak bisa lagi aku menganggur. Badanku akan menjadi sakit dan rentan terhadap penyakit bila aku berdiam diri di rumah, apalagi hanya tergolek di tempat tidur. Fisikku harus dibawa beraktifitas, dibawa bergerak agar aku keluar keringat dan tubuhku semua tergerak seperti seorang atlet melakukan aktifitas olahraga.
Pada suatu senja, Senin Legi, tanggal 3 Januari 2011, saag aku sendirian di pojook hutan membersihkan rumput perkebunan kelapa sawit, aku bertemu dengan seorang kakek tua bertubuh bongkok. Kakek itu bertubuh hitam legam karena terbakar matahari, memakai topi caping, berbaju sorjan Jawa dan bercelana sedengkul membawa tongkat kayu setigi. Dengan nafas terengah-engah, Sang Kakek mendekati aku. Aku lalu menyapanya dan mengucapkan salam hormat kepadanya sebagai orang tua.
Kakek itu lalu mengucapkan salam kembali kepadaku dan meminta izin untuk duduk di tanah dekatku kerja, sambil membuka topi caping lalu mengipas-ngipaskan topi itu ke mukanya yang terlihat kepanasan. "Anak ini seorang wanita yang kuat, bekerja keras setiap hari untuk menghidupi anak-anaknya. Padahal, tidak bekerja pun, Anak ini sudah ada yang bisa menanggung, yaitu anaknya yang bernama Halimah Sakdiyah dan menantunya yang bernama Mukhlis di Pandeglang itu", kata Sang Kakek.
Mendengar kaata-kata yang dihembuskan dari bibirnya yang bergetar, aku tersentak kaget. Bagaimana bisa kakek-kakek yang tidak aku kenal itu, mengenal persis keluargaku, bahkan tahu betul tentang keberadaan anak dan menantuku di Pandeglang, Banten.
"Maaf, kakek kok tahu persis tentang anak dan menantuku di Pandeglang itu?" tanyaku, penasaran. Dengan mengeluarkan rokok daun nipah dan menyulutnya, Si Kakek lalu menceritakan, bahwa dirinya adalah Kakek dari ayahku, Haji Hamidi dan dia bernama Soeprapto Prawiro, asal Jawa Tengah, yang sudah meninggal 300 tahun yang lalu.
Duh Gusti, si kakek ini ternyata sudah almarhum dan yang hadir di depanku adalah arwah yang maujud di senja yang wingit, Senin Legi 3 Januari tersebut. Jantungku mulai bergetar, lalu beberapa saat kemudian berdegup kencang. Ada percampuran antara rasa takut, gelisah, gundah gulana dan cemas, berkecamuk jadi satu dalam batinku. Aku kepingin buru-buru pergi dair daerah itu, tetapi rasanya kakek yang mengaku masih kerabatku itu, terlalu sopan dan baik. Rasanya tidak pantas kalau aku berlari meninggalkan dia yang masih ingin terus bercerita kepadaku.
Beberapa saat kemudian, awan tiba-tiba menutupi langit dan senja pun menjadi gelap. Tidak berapa lama kemudian, petir menyambar perkebunan kelapa sawit dan sebatang pohon sawit terkena petir. Setelah api petir menyilaukan mataku, Si Kakek raib dalam hitungan detik, menghilang entah ke mana. Aku tidak tahu lagi Sang Kakek pergi ke mana dan di mana aku dapat menemukannya.
Namun, sebelum raib, saat beberapa detik setelah petir menyambar, aku mendengar pesan terakhirnya, aku disuruh menyimpan tongkat kayu stingi miliknya dan merawat tongkat itu dengan baik. Benar saja, walau Sang Kakek, kupanggil saja Mbah Prawiro menghilang, namun tongkatnya maish ada di tempat. Tongkat kayu setigi itu tertinggal dan sesuai pesan terakhirnya, aku harus menyelamatkan tongkat itu serta merawatnya.
Sesaat setelah aku mengangkat tongkat, hujan deras turun membasahi perkebunan kelapa sawit. Dalam keadaan hujan deras, anehnya, saat aku memikul tongkat itu, air hujan tidak membasahi diirku. Batinku, benarkah tongkat ini yang membuat air hujan tidak dapat menyentuhku? Lalu, karena penasaran, aku mencoba melapskan tongkat dari tanganku, melemparkannya ke batang pohon kelapa sawit. Lalu, aku keluar ke lapangan menantang hujan. Benar saja, tubuhku menjadi basah kuyup dan air hujan menyirami deras seluruh badanku.
Namun, setelah aku kembali mengambil tongkat itu, air hujan kembali tidak dapat menyentuh tubuhku. Jangankan menyirami, mendekat ke badanku pun, tidak dapat dilakukan. Bahkan, setiap jalan yang aku lalui, semuanya terbebas dari air hujan, bahkan terlihat kering dari genangan air. Aku segera pulang ke rumah dan melakukan sholat Magrib.
Habis Maghrib, aku pergi ke ATM dan berniat mengambil uang Rp 500 ribu utnuk keperluan sekolah anak-anakku keesokan harinya. Sebab aku belum gajian, di maan menerima gaji setiap hari sabtu, akhir minggu, sementara hari itu baru hari senin, yang berarti masih enam hari lagi aku baru menerima uang.
Karena tidak ada uang lagi, maka aku tepaksa ke ATM untuk mengambil uang yang tersisa Rp 5 juta di tabunganku. Karena hujan masih deras, maka aku membawa tongkat kayu setigi untuk dijadikan payung. Kayu itu aku bawa ke ATM dan menghindarkan aku dari kebasahan oleh air hujan. Sesampainya di ATM, tiba-tiba tongkat warisan gaib itu terlepas dan jatuh ke kotak ATM. Gedubrak, bunyinya. Aku tersentak, ketakutan kalau kaca LCD ATM milik Bank Mahkota Abadi itu terpecah. Tapi untunglah tdiak pecah. Jangankan sampai pecah, baret-baret pun, tidak terlihat.
Namun, jantungku berdetak hebat, saat aku usai memencet nomo rpIN ku dan data saldo keluar. Setelah aku memencet tombol untuk memeriksa saldo, keluarlah angka yang menyentak batinku. Uang saldoku besar sekali, Rp 5 Milyar. Angka nolnya begitu banyak dan aku nyaris pingsan dibuatnya. Karena penasaran, aku mencoba mengambil uang Rp 10 juta, per-kali ambil Rp 1.000.000, sebanyak 10 kali pencet. Uang itu semuanya keluar dan uang saldoku benar-benar Rp 5 Milyar.
Aku baru-baru pulang dengan tongkat kayu itu lagi dan segera menelpon Halimah Sakdiyah dan Mukhlis di Banten. Mukhlis dan tersentak, mereka tidak mentransfer uang sebesar itu kepadaku dan mereka belum mentransfer sama sekali setelah Rp 6 juta pemberian mereka beberapa waktu lalu. Mukhlis segera melaporkan hal itu ke bank pusat dan ternyata uang itu memang ada di dalam rekeningku.
Aliran dana Rp 5 Milyar itu datang dari seseorang yang tidak dikenal. Ada nama dan ada jalur perbankannya, tapi orang tersebut tidak dikenal sama sekali. Maka, bank pun, mensahkan uang itu sebagai uangku dan aku bebas untuk menggunakannya. Bersama Mukhlis dan Halimah, aku mencairkan uang itu untuk semuar orang miskin di Indonesia, selebihnya untuk Panti Jompo, Panti Asuhan dan rumah ibadah. Kini uang saldoku, kembali ke aslinya, yaitu kurang dari Rp 5 juta dan aku tak mau memanfaatkan tongkat itu lagi untuk mendapatkan uang gaib.
Dalam mimpiku, Mbah Prawiro datang dan memarahiku. Katanya, tongkat itu bisa digunakan untuk menarik uang alam gaib dan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
"Kau boleh menggunakan uang itu untuk kesenangan hidupmu, karena selama ini, kau sudah terlalu lama hidup susah. Tongkat itu adalah tongkat warisan sah dan dapat digunakan untuk keperluan apapun, manfaatkanlah", ungkap Mbah Prawiro, lalu menghilang dari mimpiku.
Walaupun tongkat itu sakti mandraguna dan bisa untuk mendatangkan kekayaan, namun aku belum mau memanfaatkannya. Aku takut salah dna takut keliru dalam menggunakan benda gaib itu, walau yang mewariskan telah merestui bahkan mendukungku untuk memanfaatkannya. Aku masih bekerja di perkebunan karet dan perkebunan sawit dalam keadaan hidup apa adanya. Sebab, bagiku, kebahagiaan bukan dari harta berlimpah dan mobil yang mewah, tapi kebahagiaan itu aku dapatkan karena hidupku ikhlas dan dekat dengan Allah Azza Wajalla.
Kebahagiaan itu sederhana saja, cukup makan, cukup tidur dan banyak waktu untuk menghadap Tuhan. lain dari itu, kebahagiaanku, kecil saja, yaitu saat aku melihat anak-anakku semua sehat, aku sehat dan selera makan kami cukup baik, walau hanya bersantap nasi dan sambal terasi. Tongkat kayu setigi itu, hingga kini, sesuai pesan gaib Mbah Prawiro kepadaku, tidak boleh seorang pun tahu tentang keberadaannya. Memang, anak-anakku pun, tidak ada yang mengetahui tentang eksistensi tongkat itu. Bahkan, semua orang tidak dapat melihat tongkat itu selain aku. Tongkat itu sangat gaib dan linuwih, dan hanya aku yang dapat melihat, memegang dan menggunakannya.
(Kisah ini dialami oleh Sarinah Al Belitangi, Yudhistira Manaf menulis cerita itu untuk Kita semua)
Manaf, Yudhistira. 2013. Majalah Misteri Edisi 555. Jakarta: Yayasan Sinar Berdiri Jaya.