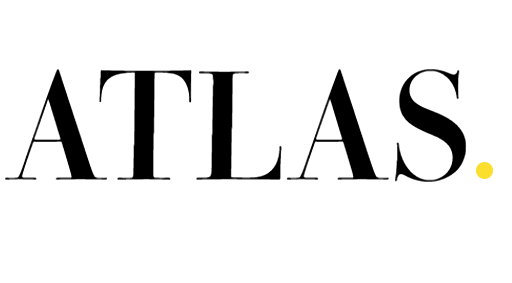|
| Gambar oleh Kurious dari Pixabay |
Jika dicermati, nyaris tidak ada presiden di republik ini yang mulus menjalankan kekuasaannya. Guncangan prahara yang menimpa mereka terkadang sangat dahsyat seperti yang dialami Presiden Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Ketiganya 'terusir' dari istana di tengah masa jabatannya. Presiden Soekarno harus meninggalkan Istana Negara setelah geger pemberontakan PKI dan pembunuhan terhadap jenderal-jenderal Angkatan Darat. Meski demikian, sebagian kalangan meyakini peristiwa 30 September 1965 itu merupakan coup d'etat terselubung yang digerakkan oleh Soeharto yang kemudian menggantikan Soekarno. Mana yang benar masih merupakan misteri. Namun yang pasti, setelah pidato pertanggung jawabannya yang dinamai Nawaksara ditolak MPRS, Bung Karno pun dipaksa meninggalkan Istana Negara.
Menyingkap Prahara Istana Negara (Part 2) - Dan sejarah berulang ketika Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun harus menerima kenyataan pahit; dilengseerkan oleh kekuatan rakyat (people power). Pak Harto tak kuasa menahan desakan rakyat yang dimotori mahasiswa. Dalam sebuah jumpa pers yang emosional pada 21 Mei 1998 Soeharto pun menyatakan dirinya mundur sebagai presiden atau dalam istilah yang sering dikemukakan Pak Harto: lengser keprabon mandheg pandhito.
Nasib tragis juga Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden ke-4 itu 'dipaksa' meninggalkan istana setelah Sidang Istimewa MPR yang dipimpin Amien Rais mencabut mandat yang diberikan. Gus Dur yang tidak terima dengan keputusan MPR sempat mengeluarkan Dekrit Presiden. Namun dekrit itu tidak mampu mencegah kejatuhan kekuasaannya. Gus Dur juga sempat muncul di depan Istana Negara hanya dengan mengenakan celana pendek untuk menarik simpati rakyat. Namun 'kutukan' Istana Negara yang tidak dilengkapi benteng itu kembali menelan korban. Gus Dur akhirnya pasrah dan menerima kenyataan pahit dilengserkan di tengah masa jabatannya.
Sedangkan BJ Habibie dan Megawati Soekarnoputri hanya menghabiskan sisa waktu pendahulunya sebagai presiden. Meski tidak sampai terusir dari istana, namun keduanya gagal merengkuh jabatan keduanya. BJ Habibie tidak ikut pemilihan presiden, yang waktu itu masih dilaksanakan oleh MPR, karena pertanggungjawabnya ditolak. Sementara Megawati kalah dalam pemilihan presiden yang untuk pertama kali digelar secara langsung.
Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Meski belum ada tanda-tanda SBY akan jatuh di tengah jalan, namun prahara yang menimpana tidak bisa dibilang ringan dari mulai maraknya bencana alam hingga 'tsunami' korupsi yang kini tengah mendapat sorotan luas. Jika tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin lilitan korupsi di Kemenpora yang menyeret Bendahara DPP Partai Demokrat M. Nazarudin dan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengimbas kemana-mana hingga ke tubir istana.
Kisruh di seputar istana tentu saja membawa dampak kepada rakyat. Negeri yang konon gemah ripah loh jinawi ini pun tidak mampu membebaskan dirinya dari kungkungan kemiskinan. Para pemimpin di negeri ini telah gagal mewujudkan amanat yang diembannya karena sibuk dengan urusan di sekitar kekuasaannya sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan kepentingan rakyat. Selama prasyarat untuk membangun kuta negara yang sesuai pakem belum terpenuhi maka kondisi ini akan terus berlanjut.
Pembangunan benteng di sekitar istana bukan untuk memisahkan penguasa dengan rakyatnya, melainkan sebagai simbol keagungan. Istana Negara yang tidak dikelilingi benteng akan kehilangan aura kedigdayaannya sehingga berpengaruh terhadap penghuninya. Benteng juga merupakan pilar ke empat dari sebuah kuta negara yang dikenal selama ini. Menghadirkan benteng di sekitar Istana Negara menjadi wajib hukumnya agar prahara para pemimpin kita segera berakhir.
KHARISMA BUNG KARNO
Jakarta sebagai kuta negara tidak terlepas dari kharisma dan kepemimpinan Presiden Soekarno. Masyarakat Jawa sangat meyakini Bung Karno mewarisi wahyu cakraningrat, kekuatan yang hanya dimiliki oleh rajha-raja tanah Jawa. Bung Karno sendiri menyadari hal itu. Salah satunya tertuang dalam gagasan pembuatan monumen nasional (Monas) yang berbentuk lingga dan yoni sekaligus. Kawasan Monas sekaligus dijadikan sebagai alun-alun.
Soekarno juga membangun Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan Gereja Kathedral yang sudah ada sebelumnya. Pembangunan tempat ibadah tersebut untuk memenuhi konsep Macapat tata ruang jawa yakni terintegrasinya kawasan pemerintahan (istana), tempat peribadatan (masjid/gereja) dan publik (alun-alun). Namun seperti disinggung di atas, ada satu hal yang 'dilupakan' Soekarno untuk memenuhi empat unsur dalma folosofi kuta negara uakni benteng. Semua kawasan kuta negara sejak kerajaan Majapahit sampai Mataram bahkan Yogyakarta dan Solo, terdapat benteng yang mengelilingi istana. Untuk menyempurnakan konsep kuta negara tersebut tidak lain mesti dibangun benteng yang mengelilingi kompleks Istana Negara.
Selain itu letak masjid juga seharusnya berada di sebelah barat alun-alun dan pusat pemerintahan berada di sebelah selatan. Namun Masjid Istiqlal berada di sebelah Timur Laut. peletakan semacam itu dimaksudkan agar sumbu bangunan masjid dan pusat pemerintahan bertemu di bagian tengah alun-alun. Kesatuan struktur dari bangunan pusat pemerintahan dan masjid bisa dianggap sebagai representasi terpangkunya jagat oleh dua struktur kelembagaan yang mengatur kehidupan manusia.
SEKILAS ISTANA NEGARA
Istana Negara, sebagaimana dikutip dari Wikipedia, ebrada dalam satu komplek dengan Istana Merdeka yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. dua buah bangunan utama ini memiliki luas 6,8 hektar dan terletak di antara Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Veteran, serta dikelilingi oleh sejumlah bangunan yang sering digunakna sebagai tempat kegiatan kenegaraan.
Dua bangunan utama adalah Istana Merdeka yang menghadap ke Taman Monumen Nasional (Jalan Medan Merdeka Utara) dan Istana Negara yang menghadap ke Sungai CIliwung (Jalan Veteran). Sejajar dengan Istana Negara ada pula Bina Graha. Sedangkan di sayap barat antara Istana Negara dan Istana Merdeka, ada Wisma Negara.
Pada awalnya di kompleks Istana di Jakarta ini hanya terdapat satu bangunan, yaitu Istana Negara. Gedung yang mulai dibangun 1796 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dan selesai 1804 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes Siberg ini semula merupakan rumah peristirahatan luar kota milik pengusaha Belanda, J A Van Braam. Kala itu kawasan yang belakangan dikenal dengan nama Harmoni memang merupakan lokasi paling bergengsi di Batavia Baru.
Pada tahun 1820 rumah peristirahatan van Braam ini disewa dan kemudian dibeli (1821) oleh pemerintah kolonial untuk digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta tempat tinggal para gubernur jenderal bila berurusan di Batavia (Jakarta)/ Para gubernur jenderal waktu itu kebanyakan memang memilih tinggal di Istana Bogor yang lebih sejuk. Tetapi kadang-kadang mereka harus turun ke Batavia, khususnya untuk menghadiri pertemuan Dewan Hindia, setiap Rabu.
Rumah van Braam dipilih untuk kepala koloni, karena Istana Daendels di Lapangan Banteng belum selesai. Tapi setelah diselesaikan pun gedung itu hanya dipergunakan untuk kantor pemerintah.
Selama masa pemerintahan Hindia Belanda, beberapa peristiwa penting terjadi di gedung yang dikenal sebagai Istana Rijswijk (namun resminya disebut Hotel van den Gouverneur Generaal, untuk menghindari kata istana) ini. Di antaranya menjadi saksi ketika sistem tanam paksa atau cultuur stelsel ditetapkan Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch. Lalu penandatanganan pPersetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947, yang pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan pihak Belanda diwakili oleh H. J. van Mook.
Pada milanua bangunan seluasm 3.375 m2 beraksitektur gaya Yunani Kuno ini bertingkat dua. Tapi pada 1848 bagian atasnya dibongkar dan bagian depan lantai bawah dibuat lebih besar untuk memberi kesan lebih resmi. Bentuk bangunan hasil perubahan 1848 inilah yang bertahan sampai sekarang tanpa ada perubahan yang berarti.
Sebagai pusat kegiata pemerintahan negara, saat ini Istana Negara menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, antara lain pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional, kongres bersifat nasional dna internasional, dan jamuan kenegaraan.
Karea Istana Rijswijk mulai sesak, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal J.W. van Lansberge tahun 1873 dibangunlah istana baru pada keveling yang sama, yang waktu itu dikenal dengan nama Istana Gambir. Istana yang diarsiteki Drossares pada awal masa pemerintahan RI sempat menjadi saksi sejarah penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh Pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949. Waktu itu RI diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan kerajaan Belanda diwakili A.H.J Lovinnk, wakil tinggi mahkota Belanda di Indonesia.
Dalam upacara yang mengharukan itu bendera Belanda diturunkan dan Bendera Indonesia dinaikkan ke langit biru. Ratusan ribu orang memenuhi tanah lapangan dan tangga-tangga gedung ini diam mematung dan meneteskan air mata ketika bendera Merah Putih dimnaikkan. Tetapi, ketika Sang Merah Putih menjulang ke atas dan berkibar, meledaklah kegembiraan mereka dan terdengar teriakan: Merdeka! Merdeka! Sejak saat itu Istana Gambir dinamakan Istana Merdeka.
Sehari setelah pengakuan kedaulatan oleh kerajaan Belanda, pada 28 Desember 1949 Presiden Soekarno beserta keluarganya tiba dari Yogyakarta dan untuk pertama kalinya mendiami Istana Merdeka. Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di Istana Merdeka pertama kali diadakan pada 1950.
Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintahan Republik Inddonesia, sudah lebih dari 20 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menggunaakn Istana Merdeka sebagai kediaman resmi dan pusat kegiatan pemerintahan negara.
Sebagai pusat pemerintahan negara, kini Istana Merdeka digunakan untuk penyelenggaraan acara-acara kenegaraan, antara lain Peringatan Detik-detik Proklamasi, upacara penyambutan tamu negara, penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat, dan pelantikan perwira muda (TNI dan Polri).
Bangunan seluas 2.400 m2 itu terbagi dalam beberapa ruang. Yakni serambi depan, ruang kredensial, ruang tamu/ruang jamuan, ruang resepsi, ruang benera pusaka dan teks proklamasi. Kemudian ruang kerja, ruang tidur, ruang keluarga/istirahat, dan pantry (dapur).
Sepeninggal Presiden Soekarno, tidak ada lagi presiden yang tinggal di sini, kecuali Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno memilih tinggal di Jalan Cendana. Tapi Soeharto tetap berkantor di gedung ini dengan men-set up sebuah ruang kerja bernuansa penuh ukiran khas Jepara, sehingga disebut sebagai Ruang Jepara serta lebih banyak berkantor di Bina Graha.
Wahyono, Yon Bayu. 2012. Majalah Misteri Edisi 527. Jakarta: Yayasan Sinar Berdiri Jaya.